Ratusan warga Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, mengajukan keluhan kepada DPRD Bali terkait penguasaan tanah yang berlangsung di wilayah mereka. Dalam sebuah aksi damai yang terjadi pada hari Senin (3/2), para warga meminta dukungan untuk kembali menguasai lahan mereka yang telah dikuasai oleh investor, terutama perusahaan PT Jimbaran Hijau dan PT CTS. Dalam penguasaan ini, sekitar 280 hektar tanah di seputaran Desa Jimbaran terancam hilang, dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Akibat penguasaan lahan ini, sekitar 200 kepala keluarga (KK) di Desa Jimbaran saat ini terpaksa tidak memiliki hunian yang layak,” ungkap Jero Bendesa Adat Jimbaran, I Gusti Rai Dirga Arsana Putra. “Kondisi ini semakin mempersulit warga yang mencari tempat tinggal yang lebih baik, dan mereka kini harus mengontrak kos-kosan di seputaran Jimbaran.”
Dalam situasi yang memprihatinkan ini, kegemerlapan pariwisata yang terdapat di Jimbaran justru membuat banyak warga terpinggirkan. Menurut keterangan dari Bendesa Adat, banyak di antara mereka yang terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup di tengah maraknya investasi di kawasan yang mereka anggap tanah warisan.
Lebih dari 140 orang warga yang tergabung dalam Kesatuan Penyelamat Tanah Adat (KEPET ADAT) melayangkan gugatan class action terhadap beberapa perusahaan serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Sidang perdana gugatan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar pada hari yang sama dengan aksi mereka ke DPRD.
I Nyoman Wirama, Koordinator Kuasa Hukum KAPET AFAT Jimbaran, menjelaskan ada lima kelompok masyarakat yang mendukung gugatan ini. Mereka merupakan penggarap yang memiliki dokumen resmi dari desa adat, ahli waris yang memiliki bukti sah secara hukum, pemilik lahan dengan sertifikat hak milik, serta masyarakat hukum adat yang berhak atas tanah tersebut. “Kami merasa apa yang terjadi jelas merupakan ketidakadilan,” tambah Wirama.
Penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT Jimbaran Hijau dan PT CTS terjadi setelah pemerintah membebaskan tanah itu dengan alasan untuk kepentingan umum. Namun, hingga saat ini tidak ada pembangunan apapun yang terlihat, dan sebagian besar lahan justru dibiarkan terlantar. Dalam proses pembebasan yang berlangsung sejak tahun 1994, banyak warga yang merasa diusir secara represif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan etika di balik penguasaan tanah tersebut.
Mengacu pada data yang terungkap, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diduga melibatkan Badan Pertanahan Nasional, diperoleh setelah proses yang menurut warga dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar. “Lahan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat justru seperti dipergunakan untuk kepentingan bisnis pribadi,” jelas Wirama, menyoroti pelanggaran yang terus berlangsung.
Anehnya, meskipun lahan tersebut sudah berstatus terlantar, beberapa perusahaan tetap berinisiatif untuk melakukan kerjasama pengelolaan. Sebagian besar lahan dibiarkan kosong, sehingga menimbulkan kegundahan di hati masyarakat yang telah lama menggarap tanah tersebut.
Sikap agresif terhadap warga yang berusaha mempertahankan penguasaan fisik mereka terhadap lahan juga mencuat. Sering kali warga diusir dengan kekerasan, namun mereka tetap berupaya menjaga hak atas tanah yang secara turun-temurun telah mereka miliki. Warga menilai bahwa tindakan hukum yang harus diambil adalah untuk melindungi hak dan keberlanjutan hidup mereka.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana ketidakadilan dalam penguasaan lahan dapat menjadikan masyarakat yang seharusnya makmur terpaksa bergantung pada kos-kosan dan kehilangan identitas mereka sebagai pemilik tanah warisan. Perjuangan masyarakat Jimbaran kini tengah berlanjut, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan demi kelangsungan hidup mereka di tanah yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

 Megawati dan Al Gore Diskusikan Kebakaran Los Angeles di Vatikan
Megawati dan Al Gore Diskusikan Kebakaran Los Angeles di Vatikan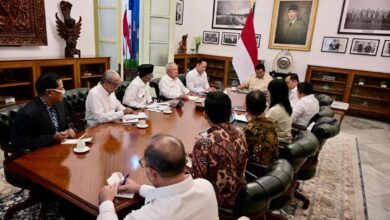 Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Dilanjutkan, Ini Harapannya!
Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Dilanjutkan, Ini Harapannya! Raih Perhatian! Megawati dan Jokowi Hadiri HUT ke-17 Gerindra
Raih Perhatian! Megawati dan Jokowi Hadiri HUT ke-17 Gerindra 7 Fakta Mengejutkan: Dua Polisi Peras Remaja Rp 2,5 Juta di Semarang!
7 Fakta Mengejutkan: Dua Polisi Peras Remaja Rp 2,5 Juta di Semarang!